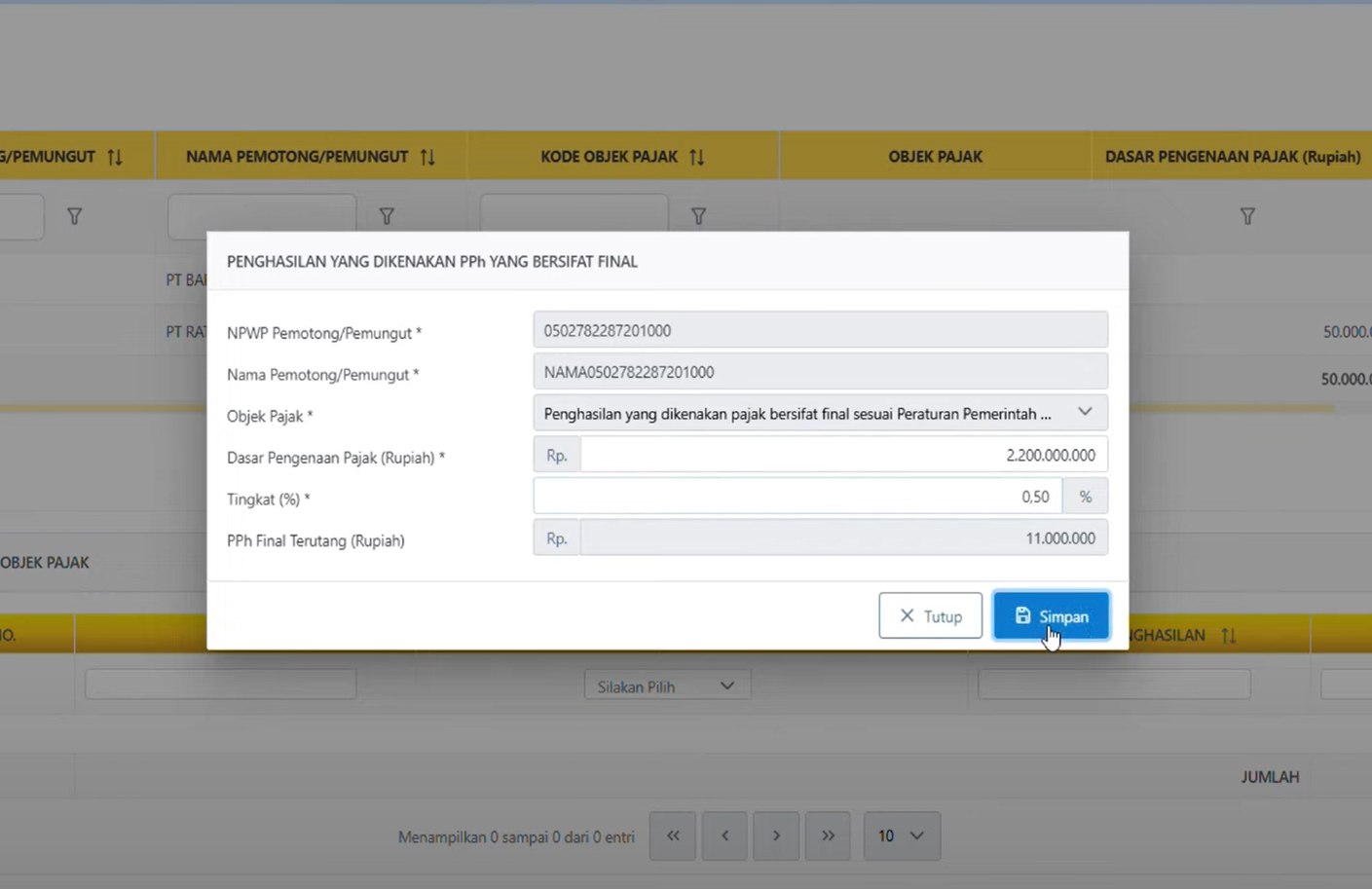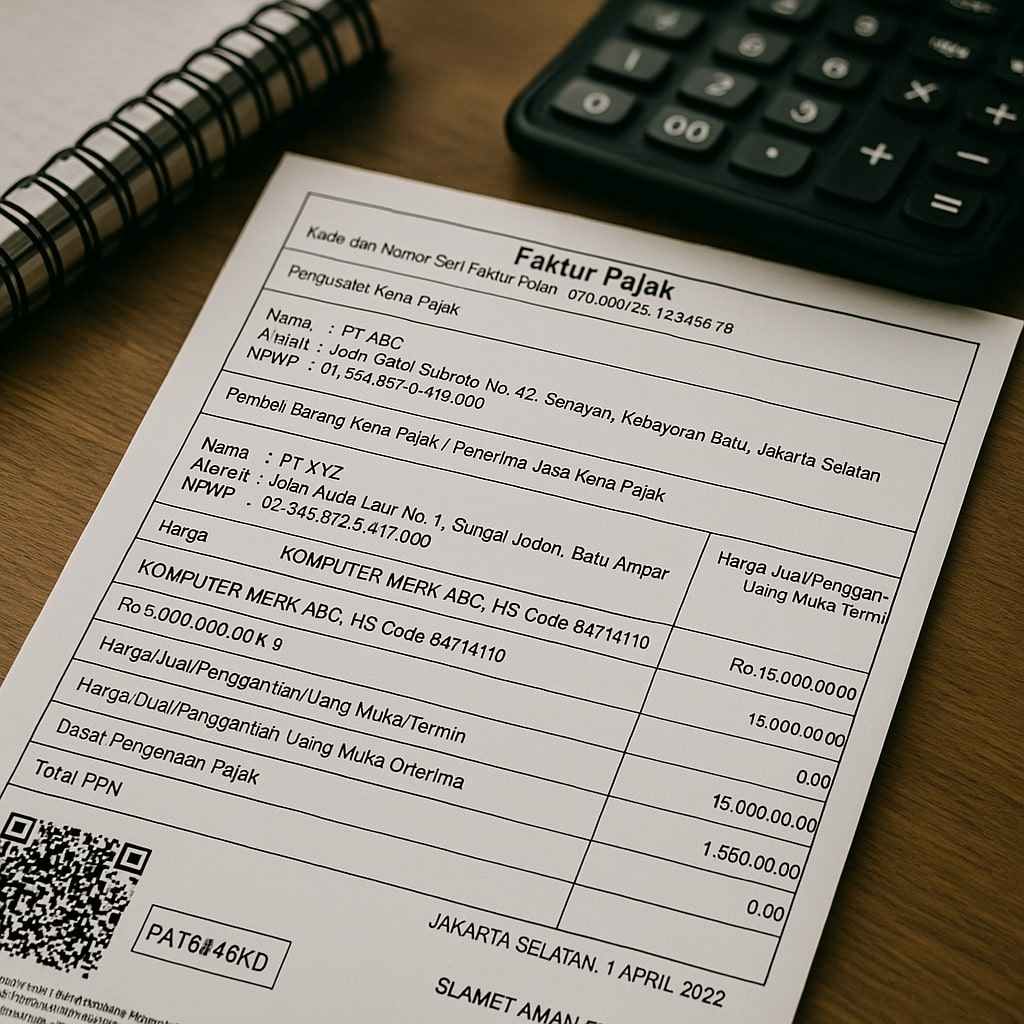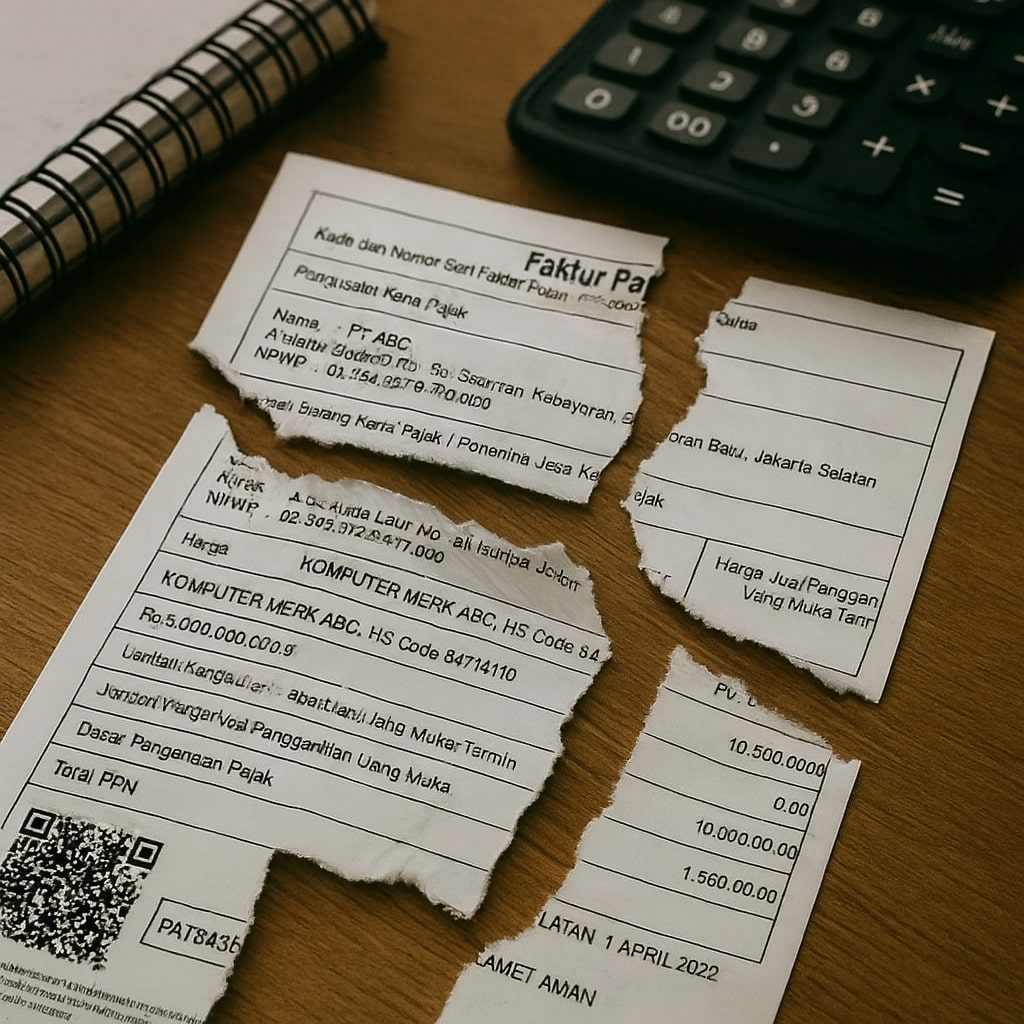Kelembagaan Keberatan Pajak: Antara Keadilan dan Konflik Kepentingan
Prinsip Trias Politica, yang diperkenalkan oleh Montesquieu (1748/1989), menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif untuk mencegah dominasi satu pihak dan menjamin keadilan. Namun, dalam sistem keberatan pajak di Indonesia, konsep ini tampaknya belum sepenuhnya diterapkan. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memiliki peran ganda, bertindak sebagai eksekutif yang melakukan pemeriksaan pajak sekaligus sebagai "hakim" yang menilai keberatan wajib pajak.Konflik kepentingan ini menimbulkan pertanyaan mendasar: dapatkah DJP bersikap objektif dalam meninjau keberatan yang diajukan terhadap keputusannya sendiri?Denda 30%: Sanksi yang Mengubah Esensi Keberatan Pajak
Salah satu perbedaan mencolok antara sistem keberatan pajak di Indonesia dan negara lain adalah pengenaan denda 30% jika keberatan wajib pajak ditolak atau diterima sebagian. Di negara lain, umumnya hanya terdapat sanksi bunga akibat keterlambatan pembayaran, bukan denda tambahan atas keputusan keberatan itu sendiri.Di berbagai negara dengan mekanisme yang mirip dengan keberatan di Indonesia, bunga keterlambatan dikenakan sebagai kompensasi atas tertundanya penerimaan negara selama proses keberatan berlangsung. Artinya, esensi sanksinya bukanlah hukuman atas keberatan yang ditolak, melainkan konsekuensi dari pembayaran pajak yang belum dilakukan tepat waktu.Di Indonesia, sebenarnya sanksi bunga juga dikenakan saat terbit putusan keberatan. Namun, bunga ini bukanlah tambahan baru, melainkan sanksi bunga pada hasil pemeriksaan (SKPKB), tetapi pembayarannya ditunda karena adanya pengajuan keberatan. Dengan kata lain, jumlahnya tetap sama dengan sanksi bunga pada hasil pemeriksaan.Hal ini diatur dalam Pasal 13 ayat (2) UU KUP, yang menyatakan:"Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar ... ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar tarif bunga per bulan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dihitung sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, dan dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan."Karena sanksi bunga ini dibatasi maksimal 24 bulan, jumlahnya tetap sama saat keputusan keberatan dikeluarkan. Dengan kata lain, dalam praktiknya tidak ada tambahan beban bunga akibat lamanya proses keberatan. Persepsi terhadap keadilan dalam sistem perpajakan memiliki korelasi erat dengan tingkat kepatuhan wajib pajak (Wenzel, 2002, 2003; Verboon & Goslinga, 2009; Saad, 2011). Dengan demikian, pengenaan sanksi harus mencerminkan keadilan dan kepastian hukum untuk menjaga kepatuhan wajib pajak. Sanksi bunga dapat dianggap adil karena esensinya bukanlah hukuman atas hasil putusan, melainkan kompensasi atas keterlambatan pembayaran yang memang wajar diterapkan dalam administrasi perpajakan. Sebaliknya, sanksi denda 30% menimbulkan ketidakadilan, terutama jika dilihat dari perspektif Trias Politica, di mana DJP berperan ganda sebagai pemeriksa dan pemutus sengketa keberatan. Keberatan seharusnya menjadi hak wajib pajak untuk mencari keadilan, bukan beban tambahan yang membuat mereka enggan mengajukan upaya hukum.Solusi: Reformasi Menuju Sistem yang Lebih Adil
Untuk mengatasi masalah ini dan memastikan sistem keberatan pajak lebih transparan serta sejalan dengan prinsip Trias Politica, ada dua langkah reformasi yang dapat dipertimbangkan:- Membentuk Lembaga Keberatan yang Independen
Agar lebih objektif dan transparan, proses keberatan seharusnya tidak lagi berada di bawah DJP, melainkan ditangani oleh lembaga independen yang terpisah dari otoritas pajak. Dengan demikian, pemisahan peran antara eksekutif (DJP) dan yudikatif (lembaga keberatan) menjadi lebih jelas, menciptakan sistem yang lebih adil bagi wajib pajak. - Menghapus Sanksi Denda 30% dan Menggantinya dengan Sanksi Bunga
Proses keberatan seharusnya hanya menjadi mekanisme peninjauan ulang, bukan ajang pengenaan sanksi tambahan. Namun, jika sanksi denda 30% dihapus tanpa adanya sanksi bunga tambahan, ada potensi penyalahgunaan keberatan sebagai cara untuk menunda pembayaran pajak. Oleh karena itu, solusi yang lebih adil adalah menggantinya dengan sanksi bunga yang tetap berlaku selama proses keberatan, agar tetap ada insentif bagi wajib pajak untuk menyelesaikan kewajibannya tepat waktu.
keadilan , keberatan , sanksi-denda , trias-politica